
Tanggal 1 Oktober
2012. Memori kita mau tidak mau harus kembali memutar kisah untuk
mengingat sejarah pada tanggal yang sama di tahun 1965. Sebuah kup
berdarah yang telah menewaskan tujuh orang jenderal Angkatan Darat (AD)
yang kemudian diangkat menjadi Pahlawan revolusi. Peristiwa itu kemudian
kita kenal dengan nama Gestapu atau G 30 S/PKI.
Itulah peristiwa berdarah yang
paling kontroversial di Republik Indonesia. Dengan skenario matang yang
diaminkan oleh aktor-aktor politik, anak negeri kemudian melakukan
pembunuhan massal terhadap anggota, simpatisan atau yang di duga
simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) diseluruh nusantara. Dengan
stigma atheis, mereka dibabat habis, tanpa pernah di hadirkan ke
pengadilan.
Tulisan ini bukan hendak membela
PKI. Juga bukan membenarkan orang-orang yang membantai “generasi PKI”
yang disebut-sebut tidak layak hidup di bumi nusantara ini. Namun,
penulis ingin “mencolek” sedikit kesaktian Pancasila, yang hari ini,
diseluruh negeri diperingati sebagai pengulang masa, bila dasar negara
kita itu mempunyai kesaktian yang mandraguna.
Penulis masih ingat sekali,
cerita salah seorang Pak Wa (abang kandung ibu penulis) yang
menceritakan, saat 1965 itu, ketika Pancasila masih sangat sakti, dalam
waktu sekejap saja prajurit Pancasilais dan massa yang di dukung oleh
“berita provokasi” dari koran Berita Yudha, melakukan pembersihan
terhadap anasir-anasir PKI.
Maka setiap malam, di
bulan-bulan pembantaian tangisan pilu terdengar menyayat dari pinggir
lubang kuburan massal. Algojo dengan kawalan prajurit tempur, menetak
siapa saja yang diangkut bagai binatang ke kamp-kamp pembantaian.
Kisah kehebatan itu kemudian di
filemkan dan wajib tonton setiap tanggal 30 September. TVRI dengan
setianya memutar film tersebut. Dan kita, mulai anak-anak sampai lansia
disuguhkan visualisasi pemberontakan G 30 S/PKI selama berjam-jam.
Permusuhan itu semakin tertanam.
Nah, selama bertahun-tahun
(lebih kurang 30 tahun) kita terus di racun dengan kesumat dendam kepada
PKI. Sehingga kita tidak sadar, bila kesaktian Pancasila yang
diagung-agungkan itu telah secara perlahan-lahan dibelokkan oleh mereka
yang punya jabatan (baik sipil maupun militer) untuk kepentingan
kelompok maupun pribadi.
Aceh, yang juga ikutan terlibat
dalam pembersihan anasir PKI, ternyata “hana di boh yum” oleh mereka
yang ada di Jakarta. Semangat Pancasila yang selalu dikumandangkan di
setiap upacara bendera hari Senin di sekolah-sekolah dipraktikkan dalam
bentuk penghisapan terhadap Aceh.
Kala itu Hasan Tiro, deklarator
Aceh Merdeka (AM) marah dan mulai memberikan perlawanan. Sebelumnya Daud
Bereueh juga pernah melakukan hal yang sama. Lalu apa jawaban dari
perlawanan meminta keadilan dari anak negeri yang notabenenya pemilik
alam daerah yang di klaim sebagai bagian dari republik?
Serdadu, ya serdadu
bersenjatalah jawabannya. Kopassus dikirim ke Aceh untuk menghentikan
perlawanan rakyat. Padahal saat itu AM belum mengakar di tengah
masyarakat. Namun kehadiran Kopassus telah menghadirkan masalah baru.
Yaitu pembunuhan tanpa alasan atas nama menjaga kedaulatan NKRI. Ini
mengakibatkan bibit-bibit perlawanan semakin banyak lahir ke bumi Aceh.
Di sisi yang lain, kesejahteraan
tak kunjung dirasakan oleh rakyat. Semakin hari semakin banyak saja
masyarakat Aceh yang jatuh miskin, di bunuh tanpa sebab, di tolak
bekerja di instansi pemerintah, yang lebih parah lagi, peraturan
“nasional” yang bernuansa jahiliyah pun di praktekkan di Aceh, yaitu
setiap muslimah dilarang menggunakan jilbab. Sehingga banyak perempuan
muslim di Aceh yang harus memilih keluar dari sekolah umum karena pihak
sekolah tidak menerima siswa yang berjilbab.
Gelombang “Tienisasi” atau
(menjadikan semua perempuan seperti Tien Soeharto) pun semakin
meningkat. Ibu-ibu mulai dari level istri kepala lorong sampai istri
pejabat diwajibkan pakai baju kebaya dan sanggul ala Tien. Ini bentuk
penelanjangan secara terstruktur terhadap keislaman orang Aceh yang
dilakukan oleh negara.
Rakyat Aceh semakin dibuat
sakit. Gelombang perlawanan pun semakin membesar. Dukungan terhadap AM
semakin membuncah dan pelanggaran HAM secara sistematis pun dimulai.
Semua itu kemudian direkam oleh
sejarah. 1989- 1998, Daerah Operasi Militer (DOM) diterapkan di Aceh.
Kemudian dilanjutkan dengan Operasi Wibawa, Operasi Sadar Rencong I
sampai III. Operasi Cinta Meunasah I dan II, Operasi Keamanan dan
Penegakan Hukum, Darurat Militer, serta Darurat Sipil.
Pembantaian terhadap rakyat pun
semakin nyata. Sebut saja beberapa pembantaian secara brutal yaitu
tragedi Rumoh Geudong (1990-1998). KNPI (3 Januari 1999). Tragedi
Arakundo (3 Februari 1999, Simpang KKA ( 3 Mei 1999), Beutong Ateuh (23
Juli 1999), Bumi Flora (9 Agustus 2001) dan Jamboe Keupok (17 Mei 2003)
Siapa pelakunya? Semua kita tahu
tentunya. Mereka yang mengaku mencintai dan membela republik inilah
aktor utama dan juga merangkap sebagai figuran. Darah bersimbah di Aceh.
Tangisan rakyatnya tak ada yang peduli. Baik polisi maupun tentara di
masa itu telah berubah menjadi mesin pembunuh rakyat Serambi Mekkah.
Lalu satu pertanyaan mendasar,
mengapa di Aceh Pancasila gagal untuk sakti? Mengapa sila-silanya tidak
mampu memberikan perlindungan kepada segenap rakyat Aceh yang sebelumnya
telah merawat bayi Garuda ketika baru lahir? Apakah kesaktiannya telah
luntur seiring lunturnya pengaruh PKI di nusantara? Ataukah kesaktian
itu hanya dilahirkan sementara untuk membabat habis PKI yang notabenenya
musuh bebuyutan militer di masa itu? Walllahua'lam
Penulis wartawan The Globe Journal, peminat masalah sosial dan politik.
*Sumber: THE GLOBE JOURNAL
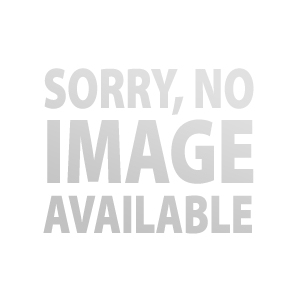
0 comments:
Post a Comment
komentar anda...