KEDUA lelaki bersaudara itu bertatapan. Lagu yang baru saja mereka dengar dari tape recorder membuat keduanya penasaran. Begitu lagu hampir usai, dengan refleks jemari Jauhari Samalanga, salah seorang di antaranya, menekan tombol rewind, membiarkan pita kaset memutar balik, kemudian menekan tombol play. Lagu itu mengalun lagi.
Nyawoung di ba eh bukon beubarang/ Jikalon badan teu eh terhanta/ Umu lhe uroe jih tanpa badan/ Keu dah bak Tuhan lon mohon pinta/ Ya Tuhanku ya Tuhan kamoe/ Izin ulon wo u bak anggota (Nyawa ditarik oh amatlah pedih/ Melihat jasad tidur telentang/ Selama tiga hari terpisah dari badan/ Kepada Ilahi dia meminta/ Ya Tuhanku ya Tuhan kami/ Izinkan hamba kembali ke jasad semula).
Lagu itu belum pernah mereka dengar. Dinyanyikan dengan penuh penghayatan oleh seorang pelantun bersuara merdu yang juga tak mereka kenal. Kaset yang mereka putar tanpa pembungkus. Itu pun nyaris hancur ketika ditemukan Joe–panggilan sehari-hari Jauhari– di toko alumunium Apollo pada suatu siang di awal September 1997.
Udara Takengon berhembus panas saat itu. Bukan hanya cuaca yang tak ramah tapi kondisi di Aceh memang sedang gerah. Tuntutan pembebasan Aceh dari status Daerah Operasi Militer (DOM), atau dikenal dengan nama Operasi Jaring Merah, tengah marak. Mahasiswa berdemonstrasi di jalan-jalan, aktivis hak asasi manusia menggelar panggung orasi di mana-mana. Sepulang memenuhi undangan wawancara interaktif di Radio Rimba Raya Takengon seputar masalah seni di Aceh, Joe menyempatkan diri mampir ke Pasar Inpres Takengon. Sudah lama dia mendengar kabar tentang toko alumunium Apollo yang selain menjual alumunium dan mebel juga menjual aneka barang bekas, termasuk kaset-kaset lama dari berbagai daerah.
Jam di tangan Joe menunjukkan angka 12.30. Perutnya keroncongan ketika dia akhirnya sampai di toko Apollo. Toko itu penuh tumpukan kayu yang berdebu, kursi-kursi yang belum dicat, dan kilauan alumunium. Langsung saja Joe menanyakan kaset-kaset bekas.
“Kasetnya banyak kali tapi dah hancur semua. Ada kaset lagu Padang, Jawa, Batak, Sunda. Aku saja nyaris tak percaya kalau ada kaset lagu Acehnya kan?” ujarnya dengan logat Aceh yang cukup kental.
Oleh penjualnya, di atas masing-masing kaset bekas itu ditempelkan label yang menginformasikan jenis dan dari daerah mana lagu itu berasal. Setiap ada yang bertuliskan Aceh, Joe mengambilnya. Harganya Rp 1.000. Joe membeli empat kaset; dua kaset biasa dan dua kaset lain berisi lagu yang biasa dipakai untuk mengiringi Tari Seudati.
Sesampainya di rumah, Joe pun terhenyak saat menyimak seluruh isi kaset itu. Lagu-lagu lawas yang lama tak didengarnya kembali menyapa telinganya. Lagu nina bobo “Dododaidi,” yang biasa dilantunkan para mamak (ibu) di Aceh untuk mengantar tidur anaknya; “Panglima Prang,” yang penuh semangat, serta “Prang Sabee” (Perang Sabil) yang menghentak. Dan ada satu lagu yang sama sekali asing namun sangat memukaunya; sebuah lagu yang bercerita tentang banyak hal yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat Aceh sejak pemberlakuan DOM: “Nyawoung.” Syair lagu itu sangat menyentuh. Berkisah tentang nyawa, sesuatu yang membuat sebuah organisme tetap hidup. Sesuatu yang seolah sudah tak ada lagi harganya di Aceh ketika kematian menjadi begitu dekat dan orang menjadi begitu terbiasa dengannya.
Setelah mendengar lagu itu, Joe diganggu rasa penasaran. Kepada seniman yang ditemuinya di seluruh Banda Aceh, Joe menanyakan siapa penyanyi sekaligus pencipta lagu itu, di mana gerangan dia tinggal? Tapi tak seorang pun mengetahuinya. Meski kecewa, sebuah semangat tumbuh di hati Joe. Dia sudah jatuh cinta pada lagu itu. Dan dia tahu apa yang harus dikerjakannya di Jakarta, yang telah menjadi rumah keduanya sejak 1986 saat mulai kuliah di Institut Ilmu Sosial-Politik Jakarta.
Di Jakarta, Joe menemui abang yang juga rekan diskusinya, Agam Ilyas. Sejak pemberlakuan DOM, keduanya membentuk komunitas Kelompok Etnis Ujung Barat, yang kemudian berganti nama menjadi Komunitas Nyawoung –nama yang terilhami lagu “Nyawoung.” Semangat komunitas ini, kata Joe, diilhami oleh Hikayat Perang Sabee, syair yang ditulis seorang ulama Aceh bernama Haji Muhammad Pantekulu pada 1881. Terutama semangat untuk mengembalikan roh kesenian Aceh yang membela hak-hak kaum tertindas. Kaset yang Joe dapatkan di toko alumunium Apollo merupakan bagian dari upaya komunitas itu mengumpulkan aneka lagu, tari, musik dan sastra Aceh yang tercecer.
Keduanya lalu memutar kaset itu berulang-ulang, mendengarkannya dengan seksama. Keduanya memutuskan untuk mendiskusikan hal tersebut dengan rekan lainnya, Hafiz Syahnara, orang Aceh yang kebetulan bekerja di EMI Indonesia, sebuah perusahaan rekaman.
8 NOVEMBER 1999, sebuah sidang kolosal yang jarang terjadi di Aceh berlangsung. Dua juta warga Aceh dari berbagai pelosok berduyun datang ke Banda Aceh. Di depan Masjid Raya Baiturrahman mereka berkumpul untuk melangsungkan Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum Aceh dan menuntut status referendum untuk Aceh.
Joe tak hadir di sana. Dia hanya bisa melihat kejadian itu dari televisi. Namun bersama sejumlah seniman Aceh yang tergabung dalam Komunitas Nyawoung, dia sudah mempersiapkan sebuah persembahan untuk warga Aceh. Namun karena kondisi Aceh belum kondusif, persembahan itu baru diluncurkan dua bulan setelah kesepakatan jeda kemanusiaan oleh Pemerintah Negara Aceh dan pemerintah Indonesia di Jenewa pada 21 Mei 2000, dengan fasilitator Henry Dunant Center.
Di bawah bendera Joe Project dan PT Nuansa Media Pusaka Jakarta, Komunitas Nyawoung merilis album Nyawoung yang berisi 10 lagu berbahasa Aceh pada Agustus 2000. Joe Project adalah tim yang dibentuk Joe beserta teman-temannya: Agam Ilyas, Hafiz Syahnara, Dewi Juniati, dan Faidaturrajni. Joe Project mengurusi masalah distribusi dan promosi album, bukan hanya album Komunitas Nyawoung.
Begitu diluncurkan, lagu-lagu heroik dalam album Nyawoung pun membahana hampir di setiap rumah, lorong, mobil pribadi, bus antarkota, serta labi-labi (kendaraan angkutan umum) di Aceh. Bahkan radio swasta yang biasanya hanya menyiarkan lagu-lagu berbahasa Indonesia turut memutarnya.
Meski tak dilantunkan untuk menidurkan seorang anak, lagu “Dododaidi” mulai terdengar lagi.
Berijang rayeuk muda sedang/Tajak banthu prang ta bela nanggroe/ Wahai aneuk bek ta deuk le/ Bedoh sare ta bela bangsa/Bek ta taot keu darah ile/ Ada pi mate poma ka rela/ Jak lon tateh, meujak lon tateh (Cepatlah besar si kecil perkasa/ Agar dapat membantu perang membela negeri/ Wahai anak janganlah engkau berleha lagi/ Bangunlah bersama membela bangsa/ Jangan takut akan darah mengalir/ Jika mati pun bunda tlah rela/ Pergilah Nak, Bunda titahkan)
Lagu “Haro Hara,” lagu tradisional yang biasa dinyanyikan para petani di Aceh setelah panen, kini kembali menggema. Hanya saja, bait-bait syairnya telah digubah menjadi lebih heroik dan disesuaikan dengan kondisi di Aceh. Jika diterjemahkan lagu itu berbunyi:
Berdentum suara senapan di siang bolong/ Terjadi konflik dan huru-hara di negeri ini/ Kaum wanita bertanya kepada suaminya/ Suara senapan tadi, bahaya apakah gerangan?/ Di langit ada gemintang di bumi tumbuh padi/ Bulan di atas bukit berbinar cahayanya/ Negeri Aceh sekarang didera nestapa/ Orang-orang mati teraniaya/ Banyak rumah dan sekolah dihanguskan/ Setiap kampung banyak perempuan menjanda/ Betapa sakit hati dan mendidih jantung/ Inilah realitas, sahabatku ...
Ya, realitaslah yang ingin dipotret dan didokumentasikan dalam album Nyawoung.
Dengan menggabungkan kekuatan modern dan tradisional, seniman-seniman Aceh menelurkan suatu karya untuk musik Aceh. Sehingga, kendati terdengar meraung-raung, sepuluh lagu dalam album Nyawoung itu tetap kuat dalam irama perkusi rapa’i, genderang Aceh, alat tiup seurune kale, biola nandong, dan keperkasaan vokal penyanyi Aceh yang khas berirama dzikir. Tak mengejutkan jika sekitar 30 ribu kopi, dari 45 ribu kopi kaset yang diproduksi, terjual di Aceh dalam tempo enam bulan. Sebuah rekor yang sulit tertandingi dalam sejarah industri musik Aceh
Demam Nyawoung membuat Senat Mahasiswa Universitas Malikus Saleh di Lhokseumawe menggelar Festival Nyawoung, dua bulan setelah peluncuran album itu. “Nyawoung” sebagai lagu wajibnya. Tak kurang dari 50 kelompok musik tradisi mengikuti festival itu.
“Wah, ramai kali!” ujar Zufrizal, pemuda kelahiran Takengon tahun 1979, peniup seurune kale dan pemukul genderang rapa’i dari Kelompok Musik Nyawoung.
Zufrizal, atau kerap dipanggil Aleks, waktu itu masih tinggal di Aceh. Kelompoknya kala itu, Sanggar Cut Mutia, mengikuti festival itu dan kebetulan menjadi juara pertama.
Nyawoung mengubah selera musik remaja Aceh. Menurut Aleks, anak muda Aceh menjadi giat dan antusias untuk mengetahui musik tradisional. Mereka juga mulai ingin mengenal alat musik tradisional. “Saat itu kan anak-anak muda sepantaran saya di sana, maunya ya main band, main drum. Atau kalau pun mau manggul gitar, ya mereknya setidaknya Ibanezlah!” ujarnya sambil tertawa.
Jika sebelumnya mereka lebih suka musik modern, menurut Aleks, itu bisa dimaklumi karena kecenderungan pasar. “Di Aceh itu banyak beredar musik Aceh, tapi lucu banget! Ada kayak lagu India, tapi cuma liriknya doang yang Aceh. Ada juga dangdut Aceh. Mana mau kan anak muda-muda mendengar lagu lagu cinta dangdutan yang ecek-ecek? Ya tentu mereka lebih senang dengar lagu Barat atau pop Indonesia. Lagian mana tahu juga kan kita musik tradisional?”
”Tapi pas Nyawoung keluar, nuansanya beda. Anak muda mana pula yang sebelumnya mau dengar lagu kuno milik orang-orang tua zaman dulu ya? Eh, tapi kalau digarapnya asyik, modern? Justru mereka yang awalnya ngerock pada berpaling ke tradisi. Mereka ingin tahu. Kalau ada pentas (musik) rock, mereka enggak malu lagi sekarang panggul rapa’i.”
“Lirik dan lagu dalam Nyawoung memang menimbulkan rasa berani ya. Semangatnya anak muda, meski lagunya sebagian adalah lagu lama. Ya judulnya saja Nyawoung, nyawa! Sudah itu, timing keluarnya mungkin tepat. Orang Aceh memang lagi butuh sekali suasana damai. Kami sedang menuntut banyak hal waktu itu. Ya sekarang juga masih menuntut sih,” ujar Taufik Abda’, mahasiswa Universitas Abul Yatama, Aceh Besar.
Sebagaimana Aleks, Abda’ menekankan kalau kesuksesan Nyawoung sangat didukung oleh kualitas rekaman yang sempurna.
Nyawoung memang album daerah pertama yang digarap dengan standar rekaman internasional. Lihat saja studio yang menggarapnya. Bila kebanyakan penggarapan lagu daerah dilakukan di studio rumahan, pengambilan vokal Nyawoung dilakukan di studio Arci dan Studio Gin. Mixing dilakukan di Prosound. Mastering dibikin di Musica Studio. Sedang rekaman dilakukan di atas pita riil berukuran dua inci. Semuanya dilakukan dengan dana terbatas, dan hanya mengandalkan lobi Hafiz Syahnara.
Joe, Agam, dan Hafiz kemudian membentuk Joe Project yang khusus menangani produksi, promosi, dan distribusi album tersebut.
Sebagai produser, Joe tidaklah kaya. Ayah dari dua anak yang sehari-hari biasa mengendarai sepeda motor ini terpaksa harus membuat sedih istrinya, Elmini Sembiring. Uang tabungan berjumlah Rp 40 juta yang dikumpulkan Joe sejak mulai bekerja, tak jadi dibelikan mobil. Ditambah uang saweran dari Agam yang berjumlah Rp 8 juta dan Hafiz Rp 6 juta, mereka mempercepat kedatangan seniman Aceh seperti Cut Ajaika, Dedy Metazon, Dik Te’, dan Muhlis ke Jakarta untuk rekaman. Proses ini berjalan 40 hari.
Setelah proses rekaman rampung, Joe harus putar otak untuk duplikasi kaset, keperluan promosi, dan distribusi. Meminjam uang dari bank tak mungkin, karena tak punya jaminan. Mencari promotor atau sponsor juga mustahil. Orang tak kenal Nyawoung. Orang juga relatif takut untuk bergabung hanya dari mendengar kata “Aceh.” Tapi seperti mukjizat, di tengah kebingungan itu, istri Joe menemukan sebuah polis deposito yang terselip di antara tumpukan kertas. Deposito yang ketika dicairkan berjumlah Rp 30 juta itulah yang mengantarkan Nyawoung ke pendengarnya di pelosok Aceh, bahkan di Jepang dan Amerika.
Total jenderal album Nyawoung menghabiskan biaya tak kurang dari Rp 125 juta.
Namun pengorbanan itu tak sia-sia. Ketika berkunjung ke Aceh pada Februari 2001, saya bisa merasakan antusiasme warga Aceh terhadap kehadiran Nyawoung. Saat bertanya kaset apa yang identik dan menggambarkan Aceh, wartawan, pejabat pemerintah, bahkan tukang becak mesin menyebut Nyawoung.
Tapi sukses itu rupanya tak diraih dengan mudah. Sejak Joe menemukan sebuah kaset di toko Apollo, diskusi dengan beberapa seniman Aceh dilakukan dengan intensif. Joe mulai mengumpulkan lagu tradisi dan kemudian memilihnya. Dia juga mencari penulis lirik yang masih setia pada tradisi penulisan syair khas Aceh. Dan itu tidaklah mudah. Selain banyak penulis Aceh sudah meninggalkan khasanah itu, keberadaan mereka pun terisolisasi sebagai akibat dari pertikaian bersenjata di Aceh. Demikian juga ketika harus memilih penyanyi. Untunglah Muhlis, seniman tradisi Aceh yang juga pengajar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, bersedia menyumbangkan vokalnya.
Namun masalah belum selesai, meski penggarapan album sudah rampung. Ini berkaitan dengan hak cipta. Seluruh personel yang terlibat dalam penggarapan Nyawoung merasa tak enak karena penulis dan pencipta lagu “Nyawoung” belum diketahui. Padahal jelas-jelas lagu tersebut menjadi judul album, dan bahkan kelak nama Nyawoung diproklamasikan sebagai nama komunitas mereka. Untuk sementara diputuskan lagu itu memakai kopi sementara yang haknya berada di tangan produser sampai penciptanya ditemukan.
Dan menjelang akhir Desember 1999, misteri itu pun terbongkarlah.
Suatu sore, Muhlis berkunjung ke rumah saudaranya di Bekasi. Bunda, begitu biasa perempuan itu dipanggil, menanyakan apa yang dilakukan Muhlis di Jakarta. Muhlis mengeluarkan kaset yang berisi suaranya. Ketika diputar, lagu pertama dalam album itu langsung membuat Bunda melafalkan Istighfar karena kaget. Muhlis ikut kaget. Ternyata Bunda mengenali lagu “Nyawoung” sebagai lagu yang biasa diajarkan dan dilantunkan Di Husein, guru mengajinya, dulu sewaktu di Banda Aceh. Di Husein, seniman unik yang lebih memilih menjadi guru mengaji dan menyebarkan syairnya kepada para muridnya, itulah pencipta lagu tersebut. Dia kini sudah meninggal dunia. Menurut Bunda, Di Husein selalu menyanyikan lagu tersebut setelah shalawat dan puji-pujian sebagai penutup setiap pengajian. Maksudnya untuk mengingatkan murid-muridnya akan kematian yang begitu menyedihkan dan bisa datang kapan saja.
Berbekal alamat dari Bunda, Muhlis berangkat ke Banda Aceh untuk menemui Maswiyah, istri Di Husein.
SIANG begitu terik di sebuah pasar di daerah Pidie pada pertengahan Mei 2001. Sebuah truk tronton yang berisi beberapa orang tentara memasuki pasar. Tentara bukanlah hal asing. Hampir tiap hari orang di Aceh melihatnya mondar-mandir. Tapi tetap saja para pedagang awas. Biasanya ada sesuatu yang akan terjadi. Benar saja, tentara meminta para pemilik toko kaset di sekitar pasar mengeluarkan semua kaset berbahasa Aceh. Lantas, “Nyawoung! Mana kaset Nyawoung?!”
Kaset-kaset itu disita, kemudian dibakar di depan toko.
Kejadian itu bukanlah yang pertama. Sebelumnya hal yang sama terjadi juga di pedalaman Aceh Tengah dan Aceh Utara. Yang dikhawatirkan akhirnya terjadi juga: lagi-lagi pemberangusan!
Lagu-lagu di Aceh memang cenderung bertema kritik sosial dan moral. Itu sudah terlihat jauh sebelum pemerintah Indonesia menerapkan DOM pada Mei 1989. Lagu “Jen Jen Jok,” dinyanyikan seniman A. Bakar Ar, misalnya, menyindir sikap orang Aceh yang tak lagi seperti orang Aceh, meninggalkan tradisi leluhur. Atau lihat lagu-lagu lain, masih milik A. Bakar Ar, yang dari judul-judulnya saja sudah tercium muatan kritik seperti “Operasi Jilbab,” ”Putoh Asa,” ”Kaco Balo,” dan “Peristiwa Simpang KKA.”
Sejak DOM berlaku, penurunan kualitas lirik dalam lagu-lagu Aceh sangat terasa. Selain karena represi militer, gempuran industri musik komersial juga memengaruhi.
Keberanian seniman Aceh mulai terdongkrak lagi sejak tuntutan pembebasan Aceh dari DOM berlangsung, terutama menjelang reformasi pada awal 1998. Dan warga rupanya sudah menantikannya. Penyanyi senior Yacob Taelah membuat lagu “Referendum” yang dianggap banyak orang sebagai karya yang menyerempet maut. Lagu itu digandrungi warga. Demikian juga karya penyanyi lain seperti Yusbi Yusuf, pelantun dan pencipta lagu “Tragedi Arakundoe,” ”Sidang Jenewa,” dan “Aceh Lam Duka.” Pula tak ketinggalan Yuldi Prima dan A. Kardinata. Seiring dengan itu, lagu “Nyawoung” yang dianggap mampu membuat gempar warga Aceh, ternyata membuat gentar juga para penguasa di Aceh yang kemudian memberangusnya.
“Memangnya berapa persen sih bapak-bapak militer itu yang orang Aceh? Apa mereka mengerti? Itu kan lagu mamak-mamak kita. Dinyanyikannya juga di pengajian kok,” ujar Joe.
Seperti kebanyakan karya, ketika telah diluncurkan ke publik, adalah hak publik untuk menerjemahkan, termasuk memahami secara personal, apa yang mereka tangkap dari syair sebuah lagu. “Tak bisa kan kita mengatur pikiran orang?” ujar Joe agak jengkel.
Menurutnya, dari awal komunitasnya merilis Nyawoung untuk seluruh warga Aceh. Jika institusi militer Indonesia menganggap lagu-lagu itu menyulut semangat Gerakan Aceh Merdeka (GAM), gerakan perlawanan yang menuntun kemerdekaan Aceh, itu bukan tujuan mereka.
“Melihat anak Soeharto kaya kali, Iwan Fals juga bikin ‘Bento’ kan?” ujar Joe. “Ya kita lihat pengungsi, kita bikin lagu ‘Untong Kamoe Nyoe’ juga. Kenapa harus marah?”
“Untong Kamoe Nyoe” adalah salah satu lagu yang terdapat dalam Nyawoung. Berkisah tentang para pengungsi yang tak bisa kembali ke kampung halaman karena segalanya musnah. Diibaratkan, kepergian mereka yang terpaksa dari tempat tinggal, dikarenakan perseteruan dua burung yang sangat kuat.
Namun, Joe dan Komunitas Nyawoung tak mau terjebak dalam kemelut politik yang berkepanjangan. Setelah mendengar laporan dari beberapa orang di Aceh tentang pembredelan Nyawoung, distribusi pun dihentikan. Nyawoung pun tak lagi diproduksi meski permintaan terus berdatangan.
“Bukannya kami takut. Tapi dari awal kita sudah tahu kalau yang mau kita lakukan hanyalah berkesenian. Kita tidak mau berpolitik,” kata Agam yang langsung diamini Joe.
“Konsep yang dikembangkan dalam album Nyawoung itu kan memperkenalkan kembali Aceh kepada orang Aceh. Di Aceh itu dulu ada prang, itu kenyataan. Dan sekarang Aceh masih perang, itu juga kenyataan,” ujar Joe. “Kalau kita takut kita pasti tak bikin album kedua kan?”
Lagu-lagu dalam Nyawoung tak hanya bisa didengar di Aceh. Radio dan televisi nasional pun kerap menjadikannya sebagai ilustrasi musik untuk pemberitaan yang berkenaan dengan Aceh. Tak heran kalau Metro TV, yang ketika itu akan membuat program “Aceh Meretas Jalan Baru” sebanyak 21 episode, meminta kelompok musik dari Komunitas Nyawoung untuk membuat ilustrasi musik. Joe langsung mengiyakan. Dengan harga kontrak Rp 750.000 per epsiode, pada pertengahan September 2001 mereka mulai menggarapnya.
Dari ilustrasi musik yang telah terbikin itu dipilih lima lagu yang kemudian, bersama lima lagu tradisi yang direkam pada Juni 2002, dibuatlah album kedua bertajuk World Music From Aceh, dengan lagu andalan “Bungong.”
Berbeda dari Nyawoung yang memadukan musik modern dan tradisional, kali ini konsep World Music From Aceh murni tradisi. Tak ada penggunaan musik elektrik kecuali akustik gambus melayu pada salah satu lagu.
Perbedaan lain ada pada pengisi suaranya. Muhlis, sang vokalis, terserang stroke. Sebagai penggantinya dipilihlah Marzuki Hasan, dosen Jurusan Tari Fakultas Seni Pertunjukan di Institut Kesenian Jakarta, yang juga ketua kelompok tari Paduraksa. Marzuki Hasan, kerap dipanggil Pak Uki, dikenal sebagai aneuk dhiek atau penyanyi pengiring pada Tari Seudati. Kekhasan vokal serta kemahirannya menari telah membawa Pak Uki berkeliling dunia. Kehebatan ba’eu (suara khasnya) yang bisa melengking tinggi seperti suara nelayan yang pilu ketika memanggil temannya di antara suara debur ombak, pernah direkam oleh manajemen Michael Jackson di Musica Studio, Jakarta.
Penambahan personel juga dilakukan. Kali ini De’Gam, Aleks, Firman, M. Taufik, dan sejumlah seniman muda Aceh bergabung meramaikan dentuman World Music From Aceh.
Tanpa promosi dan hanya menghabiskan Rp 40 juta, album itu dirilis pada Agustus 2002. Sepuluh ribu kopi kaset diedarkan. Hasilnya, sampai saat ini tujuh ribu kopi terjual di Aceh.
DI ACEH, lagu-lagu daerah belakangan mendapat tempat tersendiri di hati pendengar. “Rasanya tidak ada satu radio pun yang sekarang tidak menyiarkan lagu Aceh,” ujar Yusbi Yusuf, produser, penyanyi, sekaligus pencipta banyak lagu Aceh yang cukup dikenal. Dua stasiun radio di Banda Aceh, Baiturrahman dan Megah FM, bahkan hanya menyiarkan lagu-lagu Aceh pada segmen musiknya.
Namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Enam bulan sejak pemberlakuan DOM 1 pada 19 Mei 2003, Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) Nanggroe Aceh Darussalam rupanya mengendus sesuatu. Kekuatan syair yang terkandung dalam banyak lagu Aceh yang beredar di pasaran membuat gerah penguasa setempat. Dari penelusuran tim acehkita.com, sebuah situs yang khusus memberitakan perkembangan Aceh, disinyalir banyak lagu bernuansa tradisional yang diproduksi di Aceh pada lima tahun terakhir menyerempet-nyerempet kepentingan militer. Lagu-lagu tersebut umumnya mengisahkan penderitaan yang dialami warga Aceh selama konflik.
Atas inisiatif PDMD, Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom)–pengganti Departemen Penerangan–, dan Kejaksaan, dibuatlah sebuah tim khusus yang menyeleksi syair lagu-lagu yang beredar di Aceh. Seniman tak dilibatkan di dalamnya. Wakil Komandan Satuan Tugas Penerangan PDMD Letkol CHB Firdaus mengatakan, pembentukan tim ini dilakukan berdasarkan sejumlah analisis. Di antaranya kecenderungan karakteristik warga Aceh zaman dulu yang masih melekat di zaman kini. “Orang Aceh zaman dulu yang ketika hendak berperang seringkali dimotivasi, salah satunya dengan syair-syair yang sifatnya heroik," ujarnya.
Berdasar hasil seleksi itulah, PDMD memanggil sejumlah produser, penyanyi, dan pencipta lagu. Namun meski lagu-lagu Nyawoung disinyalir PDMD sebagai lagu yang mengandung propaganda GAM, Joe sebagai produsernya tak dipanggil. Komunitas Nyawoung sendiri memang tak bermarkas di Aceh, melainkan di Jakarta.
Komandan tim bentukan PDMD untuk operasi kaset dan video compact disk (VCD) lagu Aceh Letkol Jerry Patras mengatakan, maksud pemanggilan tersebut tak lain untuk memberi masukan dan berkonsultasi. “Kami tidak melakukan pelarangan!” tegasnya.
Hal tersebut diakui Yusbi Yusuf. Katanya, yang dilakukan di gedung Media Center Dinas Infokom saat itu adalah klarifikasi atas sejumlah lagu yang diperkirakan berisi propaganda GAM.
Pada pertemuan pertama, 4 November 2003, sekitar 20 produser dikumpulkan. Ada tiga buah lagu yang dianggap bermasalah, yakni “Nanggroe Muerdeka“ karya Yusbi Yusuf, “Ujung Blang” karya penyanyi Kadri, dan “Peristiwa Guha Tujuh” yang diproduksi Nakri Production.
Yusbi mengaku kaget saat kali pertama menerima surat pemanggilan bernomor 01/TCV/2003 dari PDMD. “Untungnya di bawah surat itu disebut Infokom juga kan? Kalau surat itu hanya pemanggilan dari PDMD saja? Wahh…”
Semua orang di Aceh tahu kalau setiap pemanggilan dilakukan PDMD maka pemanggilan itu bersifat kriminal atau sesuatu yang mengarah pada kekerasan. Sekali pergi, kebanyakan jarang ada yang kembali.
Selama proses penelitian tim bentukan PDMD, Yusbi kebat-kebit dan sudah membayangkan kalau enam album miliknya yang berjumlah 10 ribu kaset bakal ditarik dari pasaran. Namun setelah klarifikasi dengan PDMD, rupanya terjadi salah tafsir atas “Nanggroe Meurdeka,” lagu dalam album Musibah volume 5, yang diciptakan dan dilantunkan Yusbi. Tim penyeleksi mengira judul lagu itu berarti “Nanggroe Aceh Meurdeka.” Padahal, menurut Yusbi, tak ada maksud itu ketika menciptakannya. “’Nanggroe Meurdeka’ itu justru menggambarkan kalau Aceh itu amat sangat merdeka. Tidak ada hukum. Itu semacam kritik sosial. Sama sekali bukan provokasi, propaganda, atau apapun yang ditafsirkan oleh berbagai kalangan. Menurut saya jauh sekali dari permintaan Aceh Merdeka.”
Mari kita simak syairnya:
Keubit Aceh nyoe merdeka/ Cukop bebaih hana bataih hukom tanlena/ Soe nyang beuhe soe nyang teuga, nyang nyang mat kuasa/ Rakyat jelata nyang tanggong bencana (Betul Aceh ini Nanggroe merdeka/ Cukup bebas, tanpa batas, hukum pun telah tiada/ Siapa yang berani, siapa yang kuat, dia yang pegang kuasa/ Rakyat jelata yang menanggung bencana)
Nak teumeutet nak seumupoh hana le so tham/ Tan keunong hukoman ureung durjana/Rumoh ditto harta jicok ureung jitikam/pelanggaran hana le jinietna (Mau membakar, hendak membunuh tak ada yang larang/ Tak pernah kena hukuman orang durjana/ Rumah dibakar, harta dirampas, orang ditikam/ Pelanggaran hak asasi manusia tak dihiraukan)
Setelah klarifikasi, di akhir pertemuan Jerry Patras menyatakan, memberi waktu dan kesempatan kepada para produser untuk menarik sendiri kaset yang menurut mereka dianggap bermasalah.
Pada pertemuan kedua, 13 November, yang dihadiri produser, penyanyi, dan pencipta lagu, dibahas tentang evaluasi dan rencana penarikan kaset serta VCD lagu-lagu yang terindikasi mengandung propaganda. Jerry Patras kini mengeluarkan blacklist sejumlah lagu yang dilarang beredar. Katanya, berdasarkan penyelidikan tim penyeleksi syair bentukan PDMD, ada lima lagu yang terindikasi dan harus ditarik dari pasar. Lagu-lagu tersebut adalah “Arakundoe” karya Yusbi Yusuf, “Simpang KKA” karya A. Bakar Ar, “Ie Mata” karya Jamaluddin, “Komandan” karya Banta Yan, dan “Jafar Sidiq” karya Jamaluddin.
Selain itu, Jerry Patras menilai sampul-sampul kaset yang dianggap bisa memancing dan mengungkit luka hati korban kemanusiaan di Aceh. Misalnya, ditemukan beberapa sampul kaset yang memuat foto-foto tragedi berdarah. Jerry Patras juga menyesalkan pemberitaan sejumlah media nasional yang dianggapnya berlebihan terhadap pemanggilan para seniman Aceh.
Tak mau ambil risiko, Yusbi menarik album Tragedi Arakundoe, yang di dalamnya terdapat lagu “Arakundoe,” miliknya. Alasannya sama seperti dengan Joe ketika memutuskan untuk tak memproduksi kembali album Nyawoung: supaya tak berdampak politis, biar tak meruncing. Yusbi juga mengaku cukup takut. Tapi dia masih berniat merilis album itu lagi, tanpa lagu “Arakundoe” yang digantinya dengan lagu baru yang akan diciptakannya.
Dampak lebih besar, seperti diungkapkan seorang produser lagu Aceh yang ogah ditulis identitasnya dalam suatu wawancara di acehkita.com, turun kegairahan mencipta lagu. “Padahal pasar memang minta lagu-lagu yang semacam itu kok. Mereka menerima dengan baik. Jika tidak ada permintaan ya enggak mungkin diproduksi, enggak bakal laku,” ujarnya.
Tak berselang setelah pertemuan itu, sejumlah seniman dari tujuh kabupaten di Aceh yang mengikuti pertemuan dengan PDMD berkumpul di rumah makan Aceh Cirasa menjelang buka puasa. Sebuah dialog dibuka pukul 16.00. Sudah lama para produser di Aceh menyadari perlunya sebuah organisasi sebagai tempat berhimpun dan menyalurkan aspirasi. Mereka juga merasa hak-hak penyanyi dan produser di Aceh belum terlindungi. Misalnya kasus pembajakan terhadap VCD lagu “Nurbanath Arhas” dari Takengon. Meski si pembajak tertangkap tangan, tapi pengadilan hanya menjatuhkan vonis tujuh hari penjara.
Selain itu, mereka juga menyadari tak punya akses dan kekuatan terhadap kebijakan penguasa setempat berkenaan dengan seni. Ini bisa dilihat dari keabsenan seniman Aceh dalam tim penyeleksi syair yang ironisnya, dampaknya sangat berpengaruh pada kehidupan berkesenian di Aceh.
Dari alasan-alasan itulah seluruh produser dan penggiat seni di Aceh sepakat membentuk Asosiasi Industri Rekaman Aceh. Ketuanya Yusbi Yusuf, pemilik Pas Record yang memang sudah malang-melintang di industri musik di Aceh.
Mendengar pemanggilan sejumlah rekannya, di Jakarta Joe menulis sebuah artikel tentang kondisi Aceh dan berkeseniannya, serta perjalanan pelarangan seni di Aceh. Artikel itu dimuat di acehkita.com. Hanya saja, meski pemanggilan itu jelas berupaya menghambat kreativitas, Joe melihat ada perbaikan yang dilakukan penguasa setempat. “Setidaknya sekarang tercipta dialoglah! Tidak main bredel seperti perlakuan kepada album Nyawoung saya dulu, kan?” ujarnya.
Di Jakarta Joe dan kawan-kawannya di Komunitas Nyawoung sering berkumpul di Taman Mini Indonesia Indah. Tepatnya di anjungan Nanggroe Aceh Darussalam. Setidaknya ada 50 orang yang bergabung dengan komunitas ini. Itu termasuk 13 seniman tradisi Aceh yang secara bergantian manggung untuk Nyawoung.
Ketika ditanya apakah tak khawatir Nyawoung dianggap sebagai komunitas provokator dari Jakarta yang mengatasnamakan seni, Agam menjawab dengan tenang, “Mereka bisa lihat, kita enggak bikin bom kok! Kita bikin musik Aceh!”
Kini, tinggal bagaimana Joe, Agam, dan teman-temannya menghadapi tantangan ke depan yang tak ringan. Pasar musik Aceh, menurut Yusbi Yusuf, cukup jenuh dengan lagu-lagu heroik atau patriotik. Meski segmen pasarnya masih tetap ada, tapi sekarang orang lebih cenderung mendengarkan lagu-lagu Aceh populer. Misalnya lagu “Marcelina” yang dilantunkan Ramli, atau lagu-lagu bernafaskan Islam seperti lagu “Ainul Mardhiah” yang dinyanyikan Rafli. Dua penyanyi muda itu tengah digandrungi di Aceh saat ini.
Tapi Joe sendiri tak mau hanya terfokus ke Aceh. Dia mengaku ingin membuat musik Aceh di Amerika atau Inggris. “Itu yang orang mau kan? Orang mau dengar apapun yang berbau luar negeri di sini. Kita juga pasti didengar, asalkan bikinnya di sana kan?” ujarnya berapi-api, meski dia sadar dengan keterbatasan dana untuk mewujudkan keinginan itu. *
*) Ucu Agustin adalah kontributor Aceh Feature di Jakarta
sumber asli artikel
http://www.acehfeature.org/index.php/site/detailartikel/387/Dendang-Nyawoung-untuk-Tanah-Rencong/
Nyawoung di ba eh bukon beubarang/ Jikalon badan teu eh terhanta/ Umu lhe uroe jih tanpa badan/ Keu dah bak Tuhan lon mohon pinta/ Ya Tuhanku ya Tuhan kamoe/ Izin ulon wo u bak anggota (Nyawa ditarik oh amatlah pedih/ Melihat jasad tidur telentang/ Selama tiga hari terpisah dari badan/ Kepada Ilahi dia meminta/ Ya Tuhanku ya Tuhan kami/ Izinkan hamba kembali ke jasad semula).
Lagu itu belum pernah mereka dengar. Dinyanyikan dengan penuh penghayatan oleh seorang pelantun bersuara merdu yang juga tak mereka kenal. Kaset yang mereka putar tanpa pembungkus. Itu pun nyaris hancur ketika ditemukan Joe–panggilan sehari-hari Jauhari– di toko alumunium Apollo pada suatu siang di awal September 1997.
Udara Takengon berhembus panas saat itu. Bukan hanya cuaca yang tak ramah tapi kondisi di Aceh memang sedang gerah. Tuntutan pembebasan Aceh dari status Daerah Operasi Militer (DOM), atau dikenal dengan nama Operasi Jaring Merah, tengah marak. Mahasiswa berdemonstrasi di jalan-jalan, aktivis hak asasi manusia menggelar panggung orasi di mana-mana. Sepulang memenuhi undangan wawancara interaktif di Radio Rimba Raya Takengon seputar masalah seni di Aceh, Joe menyempatkan diri mampir ke Pasar Inpres Takengon. Sudah lama dia mendengar kabar tentang toko alumunium Apollo yang selain menjual alumunium dan mebel juga menjual aneka barang bekas, termasuk kaset-kaset lama dari berbagai daerah.
Jam di tangan Joe menunjukkan angka 12.30. Perutnya keroncongan ketika dia akhirnya sampai di toko Apollo. Toko itu penuh tumpukan kayu yang berdebu, kursi-kursi yang belum dicat, dan kilauan alumunium. Langsung saja Joe menanyakan kaset-kaset bekas.
“Kasetnya banyak kali tapi dah hancur semua. Ada kaset lagu Padang, Jawa, Batak, Sunda. Aku saja nyaris tak percaya kalau ada kaset lagu Acehnya kan?” ujarnya dengan logat Aceh yang cukup kental.
Oleh penjualnya, di atas masing-masing kaset bekas itu ditempelkan label yang menginformasikan jenis dan dari daerah mana lagu itu berasal. Setiap ada yang bertuliskan Aceh, Joe mengambilnya. Harganya Rp 1.000. Joe membeli empat kaset; dua kaset biasa dan dua kaset lain berisi lagu yang biasa dipakai untuk mengiringi Tari Seudati.
Sesampainya di rumah, Joe pun terhenyak saat menyimak seluruh isi kaset itu. Lagu-lagu lawas yang lama tak didengarnya kembali menyapa telinganya. Lagu nina bobo “Dododaidi,” yang biasa dilantunkan para mamak (ibu) di Aceh untuk mengantar tidur anaknya; “Panglima Prang,” yang penuh semangat, serta “Prang Sabee” (Perang Sabil) yang menghentak. Dan ada satu lagu yang sama sekali asing namun sangat memukaunya; sebuah lagu yang bercerita tentang banyak hal yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat Aceh sejak pemberlakuan DOM: “Nyawoung.” Syair lagu itu sangat menyentuh. Berkisah tentang nyawa, sesuatu yang membuat sebuah organisme tetap hidup. Sesuatu yang seolah sudah tak ada lagi harganya di Aceh ketika kematian menjadi begitu dekat dan orang menjadi begitu terbiasa dengannya.
Setelah mendengar lagu itu, Joe diganggu rasa penasaran. Kepada seniman yang ditemuinya di seluruh Banda Aceh, Joe menanyakan siapa penyanyi sekaligus pencipta lagu itu, di mana gerangan dia tinggal? Tapi tak seorang pun mengetahuinya. Meski kecewa, sebuah semangat tumbuh di hati Joe. Dia sudah jatuh cinta pada lagu itu. Dan dia tahu apa yang harus dikerjakannya di Jakarta, yang telah menjadi rumah keduanya sejak 1986 saat mulai kuliah di Institut Ilmu Sosial-Politik Jakarta.
Di Jakarta, Joe menemui abang yang juga rekan diskusinya, Agam Ilyas. Sejak pemberlakuan DOM, keduanya membentuk komunitas Kelompok Etnis Ujung Barat, yang kemudian berganti nama menjadi Komunitas Nyawoung –nama yang terilhami lagu “Nyawoung.” Semangat komunitas ini, kata Joe, diilhami oleh Hikayat Perang Sabee, syair yang ditulis seorang ulama Aceh bernama Haji Muhammad Pantekulu pada 1881. Terutama semangat untuk mengembalikan roh kesenian Aceh yang membela hak-hak kaum tertindas. Kaset yang Joe dapatkan di toko alumunium Apollo merupakan bagian dari upaya komunitas itu mengumpulkan aneka lagu, tari, musik dan sastra Aceh yang tercecer.
Keduanya lalu memutar kaset itu berulang-ulang, mendengarkannya dengan seksama. Keduanya memutuskan untuk mendiskusikan hal tersebut dengan rekan lainnya, Hafiz Syahnara, orang Aceh yang kebetulan bekerja di EMI Indonesia, sebuah perusahaan rekaman.
8 NOVEMBER 1999, sebuah sidang kolosal yang jarang terjadi di Aceh berlangsung. Dua juta warga Aceh dari berbagai pelosok berduyun datang ke Banda Aceh. Di depan Masjid Raya Baiturrahman mereka berkumpul untuk melangsungkan Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum Aceh dan menuntut status referendum untuk Aceh.
Joe tak hadir di sana. Dia hanya bisa melihat kejadian itu dari televisi. Namun bersama sejumlah seniman Aceh yang tergabung dalam Komunitas Nyawoung, dia sudah mempersiapkan sebuah persembahan untuk warga Aceh. Namun karena kondisi Aceh belum kondusif, persembahan itu baru diluncurkan dua bulan setelah kesepakatan jeda kemanusiaan oleh Pemerintah Negara Aceh dan pemerintah Indonesia di Jenewa pada 21 Mei 2000, dengan fasilitator Henry Dunant Center.
Di bawah bendera Joe Project dan PT Nuansa Media Pusaka Jakarta, Komunitas Nyawoung merilis album Nyawoung yang berisi 10 lagu berbahasa Aceh pada Agustus 2000. Joe Project adalah tim yang dibentuk Joe beserta teman-temannya: Agam Ilyas, Hafiz Syahnara, Dewi Juniati, dan Faidaturrajni. Joe Project mengurusi masalah distribusi dan promosi album, bukan hanya album Komunitas Nyawoung.
Begitu diluncurkan, lagu-lagu heroik dalam album Nyawoung pun membahana hampir di setiap rumah, lorong, mobil pribadi, bus antarkota, serta labi-labi (kendaraan angkutan umum) di Aceh. Bahkan radio swasta yang biasanya hanya menyiarkan lagu-lagu berbahasa Indonesia turut memutarnya.
Meski tak dilantunkan untuk menidurkan seorang anak, lagu “Dododaidi” mulai terdengar lagi.
Berijang rayeuk muda sedang/Tajak banthu prang ta bela nanggroe/ Wahai aneuk bek ta deuk le/ Bedoh sare ta bela bangsa/Bek ta taot keu darah ile/ Ada pi mate poma ka rela/ Jak lon tateh, meujak lon tateh (Cepatlah besar si kecil perkasa/ Agar dapat membantu perang membela negeri/ Wahai anak janganlah engkau berleha lagi/ Bangunlah bersama membela bangsa/ Jangan takut akan darah mengalir/ Jika mati pun bunda tlah rela/ Pergilah Nak, Bunda titahkan)
Lagu “Haro Hara,” lagu tradisional yang biasa dinyanyikan para petani di Aceh setelah panen, kini kembali menggema. Hanya saja, bait-bait syairnya telah digubah menjadi lebih heroik dan disesuaikan dengan kondisi di Aceh. Jika diterjemahkan lagu itu berbunyi:
Berdentum suara senapan di siang bolong/ Terjadi konflik dan huru-hara di negeri ini/ Kaum wanita bertanya kepada suaminya/ Suara senapan tadi, bahaya apakah gerangan?/ Di langit ada gemintang di bumi tumbuh padi/ Bulan di atas bukit berbinar cahayanya/ Negeri Aceh sekarang didera nestapa/ Orang-orang mati teraniaya/ Banyak rumah dan sekolah dihanguskan/ Setiap kampung banyak perempuan menjanda/ Betapa sakit hati dan mendidih jantung/ Inilah realitas, sahabatku ...
Ya, realitaslah yang ingin dipotret dan didokumentasikan dalam album Nyawoung.
Dengan menggabungkan kekuatan modern dan tradisional, seniman-seniman Aceh menelurkan suatu karya untuk musik Aceh. Sehingga, kendati terdengar meraung-raung, sepuluh lagu dalam album Nyawoung itu tetap kuat dalam irama perkusi rapa’i, genderang Aceh, alat tiup seurune kale, biola nandong, dan keperkasaan vokal penyanyi Aceh yang khas berirama dzikir. Tak mengejutkan jika sekitar 30 ribu kopi, dari 45 ribu kopi kaset yang diproduksi, terjual di Aceh dalam tempo enam bulan. Sebuah rekor yang sulit tertandingi dalam sejarah industri musik Aceh
Demam Nyawoung membuat Senat Mahasiswa Universitas Malikus Saleh di Lhokseumawe menggelar Festival Nyawoung, dua bulan setelah peluncuran album itu. “Nyawoung” sebagai lagu wajibnya. Tak kurang dari 50 kelompok musik tradisi mengikuti festival itu.
“Wah, ramai kali!” ujar Zufrizal, pemuda kelahiran Takengon tahun 1979, peniup seurune kale dan pemukul genderang rapa’i dari Kelompok Musik Nyawoung.
Zufrizal, atau kerap dipanggil Aleks, waktu itu masih tinggal di Aceh. Kelompoknya kala itu, Sanggar Cut Mutia, mengikuti festival itu dan kebetulan menjadi juara pertama.
Nyawoung mengubah selera musik remaja Aceh. Menurut Aleks, anak muda Aceh menjadi giat dan antusias untuk mengetahui musik tradisional. Mereka juga mulai ingin mengenal alat musik tradisional. “Saat itu kan anak-anak muda sepantaran saya di sana, maunya ya main band, main drum. Atau kalau pun mau manggul gitar, ya mereknya setidaknya Ibanezlah!” ujarnya sambil tertawa.
Jika sebelumnya mereka lebih suka musik modern, menurut Aleks, itu bisa dimaklumi karena kecenderungan pasar. “Di Aceh itu banyak beredar musik Aceh, tapi lucu banget! Ada kayak lagu India, tapi cuma liriknya doang yang Aceh. Ada juga dangdut Aceh. Mana mau kan anak muda-muda mendengar lagu lagu cinta dangdutan yang ecek-ecek? Ya tentu mereka lebih senang dengar lagu Barat atau pop Indonesia. Lagian mana tahu juga kan kita musik tradisional?”
”Tapi pas Nyawoung keluar, nuansanya beda. Anak muda mana pula yang sebelumnya mau dengar lagu kuno milik orang-orang tua zaman dulu ya? Eh, tapi kalau digarapnya asyik, modern? Justru mereka yang awalnya ngerock pada berpaling ke tradisi. Mereka ingin tahu. Kalau ada pentas (musik) rock, mereka enggak malu lagi sekarang panggul rapa’i.”
“Lirik dan lagu dalam Nyawoung memang menimbulkan rasa berani ya. Semangatnya anak muda, meski lagunya sebagian adalah lagu lama. Ya judulnya saja Nyawoung, nyawa! Sudah itu, timing keluarnya mungkin tepat. Orang Aceh memang lagi butuh sekali suasana damai. Kami sedang menuntut banyak hal waktu itu. Ya sekarang juga masih menuntut sih,” ujar Taufik Abda’, mahasiswa Universitas Abul Yatama, Aceh Besar.
Sebagaimana Aleks, Abda’ menekankan kalau kesuksesan Nyawoung sangat didukung oleh kualitas rekaman yang sempurna.
Nyawoung memang album daerah pertama yang digarap dengan standar rekaman internasional. Lihat saja studio yang menggarapnya. Bila kebanyakan penggarapan lagu daerah dilakukan di studio rumahan, pengambilan vokal Nyawoung dilakukan di studio Arci dan Studio Gin. Mixing dilakukan di Prosound. Mastering dibikin di Musica Studio. Sedang rekaman dilakukan di atas pita riil berukuran dua inci. Semuanya dilakukan dengan dana terbatas, dan hanya mengandalkan lobi Hafiz Syahnara.
Joe, Agam, dan Hafiz kemudian membentuk Joe Project yang khusus menangani produksi, promosi, dan distribusi album tersebut.
Sebagai produser, Joe tidaklah kaya. Ayah dari dua anak yang sehari-hari biasa mengendarai sepeda motor ini terpaksa harus membuat sedih istrinya, Elmini Sembiring. Uang tabungan berjumlah Rp 40 juta yang dikumpulkan Joe sejak mulai bekerja, tak jadi dibelikan mobil. Ditambah uang saweran dari Agam yang berjumlah Rp 8 juta dan Hafiz Rp 6 juta, mereka mempercepat kedatangan seniman Aceh seperti Cut Ajaika, Dedy Metazon, Dik Te’, dan Muhlis ke Jakarta untuk rekaman. Proses ini berjalan 40 hari.
Setelah proses rekaman rampung, Joe harus putar otak untuk duplikasi kaset, keperluan promosi, dan distribusi. Meminjam uang dari bank tak mungkin, karena tak punya jaminan. Mencari promotor atau sponsor juga mustahil. Orang tak kenal Nyawoung. Orang juga relatif takut untuk bergabung hanya dari mendengar kata “Aceh.” Tapi seperti mukjizat, di tengah kebingungan itu, istri Joe menemukan sebuah polis deposito yang terselip di antara tumpukan kertas. Deposito yang ketika dicairkan berjumlah Rp 30 juta itulah yang mengantarkan Nyawoung ke pendengarnya di pelosok Aceh, bahkan di Jepang dan Amerika.
Total jenderal album Nyawoung menghabiskan biaya tak kurang dari Rp 125 juta.
Namun pengorbanan itu tak sia-sia. Ketika berkunjung ke Aceh pada Februari 2001, saya bisa merasakan antusiasme warga Aceh terhadap kehadiran Nyawoung. Saat bertanya kaset apa yang identik dan menggambarkan Aceh, wartawan, pejabat pemerintah, bahkan tukang becak mesin menyebut Nyawoung.
Tapi sukses itu rupanya tak diraih dengan mudah. Sejak Joe menemukan sebuah kaset di toko Apollo, diskusi dengan beberapa seniman Aceh dilakukan dengan intensif. Joe mulai mengumpulkan lagu tradisi dan kemudian memilihnya. Dia juga mencari penulis lirik yang masih setia pada tradisi penulisan syair khas Aceh. Dan itu tidaklah mudah. Selain banyak penulis Aceh sudah meninggalkan khasanah itu, keberadaan mereka pun terisolisasi sebagai akibat dari pertikaian bersenjata di Aceh. Demikian juga ketika harus memilih penyanyi. Untunglah Muhlis, seniman tradisi Aceh yang juga pengajar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, bersedia menyumbangkan vokalnya.
Namun masalah belum selesai, meski penggarapan album sudah rampung. Ini berkaitan dengan hak cipta. Seluruh personel yang terlibat dalam penggarapan Nyawoung merasa tak enak karena penulis dan pencipta lagu “Nyawoung” belum diketahui. Padahal jelas-jelas lagu tersebut menjadi judul album, dan bahkan kelak nama Nyawoung diproklamasikan sebagai nama komunitas mereka. Untuk sementara diputuskan lagu itu memakai kopi sementara yang haknya berada di tangan produser sampai penciptanya ditemukan.
Dan menjelang akhir Desember 1999, misteri itu pun terbongkarlah.
Suatu sore, Muhlis berkunjung ke rumah saudaranya di Bekasi. Bunda, begitu biasa perempuan itu dipanggil, menanyakan apa yang dilakukan Muhlis di Jakarta. Muhlis mengeluarkan kaset yang berisi suaranya. Ketika diputar, lagu pertama dalam album itu langsung membuat Bunda melafalkan Istighfar karena kaget. Muhlis ikut kaget. Ternyata Bunda mengenali lagu “Nyawoung” sebagai lagu yang biasa diajarkan dan dilantunkan Di Husein, guru mengajinya, dulu sewaktu di Banda Aceh. Di Husein, seniman unik yang lebih memilih menjadi guru mengaji dan menyebarkan syairnya kepada para muridnya, itulah pencipta lagu tersebut. Dia kini sudah meninggal dunia. Menurut Bunda, Di Husein selalu menyanyikan lagu tersebut setelah shalawat dan puji-pujian sebagai penutup setiap pengajian. Maksudnya untuk mengingatkan murid-muridnya akan kematian yang begitu menyedihkan dan bisa datang kapan saja.
Berbekal alamat dari Bunda, Muhlis berangkat ke Banda Aceh untuk menemui Maswiyah, istri Di Husein.
SIANG begitu terik di sebuah pasar di daerah Pidie pada pertengahan Mei 2001. Sebuah truk tronton yang berisi beberapa orang tentara memasuki pasar. Tentara bukanlah hal asing. Hampir tiap hari orang di Aceh melihatnya mondar-mandir. Tapi tetap saja para pedagang awas. Biasanya ada sesuatu yang akan terjadi. Benar saja, tentara meminta para pemilik toko kaset di sekitar pasar mengeluarkan semua kaset berbahasa Aceh. Lantas, “Nyawoung! Mana kaset Nyawoung?!”
Kaset-kaset itu disita, kemudian dibakar di depan toko.
Kejadian itu bukanlah yang pertama. Sebelumnya hal yang sama terjadi juga di pedalaman Aceh Tengah dan Aceh Utara. Yang dikhawatirkan akhirnya terjadi juga: lagi-lagi pemberangusan!
Lagu-lagu di Aceh memang cenderung bertema kritik sosial dan moral. Itu sudah terlihat jauh sebelum pemerintah Indonesia menerapkan DOM pada Mei 1989. Lagu “Jen Jen Jok,” dinyanyikan seniman A. Bakar Ar, misalnya, menyindir sikap orang Aceh yang tak lagi seperti orang Aceh, meninggalkan tradisi leluhur. Atau lihat lagu-lagu lain, masih milik A. Bakar Ar, yang dari judul-judulnya saja sudah tercium muatan kritik seperti “Operasi Jilbab,” ”Putoh Asa,” ”Kaco Balo,” dan “Peristiwa Simpang KKA.”
Sejak DOM berlaku, penurunan kualitas lirik dalam lagu-lagu Aceh sangat terasa. Selain karena represi militer, gempuran industri musik komersial juga memengaruhi.
Keberanian seniman Aceh mulai terdongkrak lagi sejak tuntutan pembebasan Aceh dari DOM berlangsung, terutama menjelang reformasi pada awal 1998. Dan warga rupanya sudah menantikannya. Penyanyi senior Yacob Taelah membuat lagu “Referendum” yang dianggap banyak orang sebagai karya yang menyerempet maut. Lagu itu digandrungi warga. Demikian juga karya penyanyi lain seperti Yusbi Yusuf, pelantun dan pencipta lagu “Tragedi Arakundoe,” ”Sidang Jenewa,” dan “Aceh Lam Duka.” Pula tak ketinggalan Yuldi Prima dan A. Kardinata. Seiring dengan itu, lagu “Nyawoung” yang dianggap mampu membuat gempar warga Aceh, ternyata membuat gentar juga para penguasa di Aceh yang kemudian memberangusnya.
“Memangnya berapa persen sih bapak-bapak militer itu yang orang Aceh? Apa mereka mengerti? Itu kan lagu mamak-mamak kita. Dinyanyikannya juga di pengajian kok,” ujar Joe.
Seperti kebanyakan karya, ketika telah diluncurkan ke publik, adalah hak publik untuk menerjemahkan, termasuk memahami secara personal, apa yang mereka tangkap dari syair sebuah lagu. “Tak bisa kan kita mengatur pikiran orang?” ujar Joe agak jengkel.
Menurutnya, dari awal komunitasnya merilis Nyawoung untuk seluruh warga Aceh. Jika institusi militer Indonesia menganggap lagu-lagu itu menyulut semangat Gerakan Aceh Merdeka (GAM), gerakan perlawanan yang menuntun kemerdekaan Aceh, itu bukan tujuan mereka.
“Melihat anak Soeharto kaya kali, Iwan Fals juga bikin ‘Bento’ kan?” ujar Joe. “Ya kita lihat pengungsi, kita bikin lagu ‘Untong Kamoe Nyoe’ juga. Kenapa harus marah?”
“Untong Kamoe Nyoe” adalah salah satu lagu yang terdapat dalam Nyawoung. Berkisah tentang para pengungsi yang tak bisa kembali ke kampung halaman karena segalanya musnah. Diibaratkan, kepergian mereka yang terpaksa dari tempat tinggal, dikarenakan perseteruan dua burung yang sangat kuat.
Namun, Joe dan Komunitas Nyawoung tak mau terjebak dalam kemelut politik yang berkepanjangan. Setelah mendengar laporan dari beberapa orang di Aceh tentang pembredelan Nyawoung, distribusi pun dihentikan. Nyawoung pun tak lagi diproduksi meski permintaan terus berdatangan.
“Bukannya kami takut. Tapi dari awal kita sudah tahu kalau yang mau kita lakukan hanyalah berkesenian. Kita tidak mau berpolitik,” kata Agam yang langsung diamini Joe.
“Konsep yang dikembangkan dalam album Nyawoung itu kan memperkenalkan kembali Aceh kepada orang Aceh. Di Aceh itu dulu ada prang, itu kenyataan. Dan sekarang Aceh masih perang, itu juga kenyataan,” ujar Joe. “Kalau kita takut kita pasti tak bikin album kedua kan?”
Lagu-lagu dalam Nyawoung tak hanya bisa didengar di Aceh. Radio dan televisi nasional pun kerap menjadikannya sebagai ilustrasi musik untuk pemberitaan yang berkenaan dengan Aceh. Tak heran kalau Metro TV, yang ketika itu akan membuat program “Aceh Meretas Jalan Baru” sebanyak 21 episode, meminta kelompok musik dari Komunitas Nyawoung untuk membuat ilustrasi musik. Joe langsung mengiyakan. Dengan harga kontrak Rp 750.000 per epsiode, pada pertengahan September 2001 mereka mulai menggarapnya.
Dari ilustrasi musik yang telah terbikin itu dipilih lima lagu yang kemudian, bersama lima lagu tradisi yang direkam pada Juni 2002, dibuatlah album kedua bertajuk World Music From Aceh, dengan lagu andalan “Bungong.”
Berbeda dari Nyawoung yang memadukan musik modern dan tradisional, kali ini konsep World Music From Aceh murni tradisi. Tak ada penggunaan musik elektrik kecuali akustik gambus melayu pada salah satu lagu.
Perbedaan lain ada pada pengisi suaranya. Muhlis, sang vokalis, terserang stroke. Sebagai penggantinya dipilihlah Marzuki Hasan, dosen Jurusan Tari Fakultas Seni Pertunjukan di Institut Kesenian Jakarta, yang juga ketua kelompok tari Paduraksa. Marzuki Hasan, kerap dipanggil Pak Uki, dikenal sebagai aneuk dhiek atau penyanyi pengiring pada Tari Seudati. Kekhasan vokal serta kemahirannya menari telah membawa Pak Uki berkeliling dunia. Kehebatan ba’eu (suara khasnya) yang bisa melengking tinggi seperti suara nelayan yang pilu ketika memanggil temannya di antara suara debur ombak, pernah direkam oleh manajemen Michael Jackson di Musica Studio, Jakarta.
Penambahan personel juga dilakukan. Kali ini De’Gam, Aleks, Firman, M. Taufik, dan sejumlah seniman muda Aceh bergabung meramaikan dentuman World Music From Aceh.
Tanpa promosi dan hanya menghabiskan Rp 40 juta, album itu dirilis pada Agustus 2002. Sepuluh ribu kopi kaset diedarkan. Hasilnya, sampai saat ini tujuh ribu kopi terjual di Aceh.
DI ACEH, lagu-lagu daerah belakangan mendapat tempat tersendiri di hati pendengar. “Rasanya tidak ada satu radio pun yang sekarang tidak menyiarkan lagu Aceh,” ujar Yusbi Yusuf, produser, penyanyi, sekaligus pencipta banyak lagu Aceh yang cukup dikenal. Dua stasiun radio di Banda Aceh, Baiturrahman dan Megah FM, bahkan hanya menyiarkan lagu-lagu Aceh pada segmen musiknya.
Namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Enam bulan sejak pemberlakuan DOM 1 pada 19 Mei 2003, Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) Nanggroe Aceh Darussalam rupanya mengendus sesuatu. Kekuatan syair yang terkandung dalam banyak lagu Aceh yang beredar di pasaran membuat gerah penguasa setempat. Dari penelusuran tim acehkita.com, sebuah situs yang khusus memberitakan perkembangan Aceh, disinyalir banyak lagu bernuansa tradisional yang diproduksi di Aceh pada lima tahun terakhir menyerempet-nyerempet kepentingan militer. Lagu-lagu tersebut umumnya mengisahkan penderitaan yang dialami warga Aceh selama konflik.
Atas inisiatif PDMD, Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom)–pengganti Departemen Penerangan–, dan Kejaksaan, dibuatlah sebuah tim khusus yang menyeleksi syair lagu-lagu yang beredar di Aceh. Seniman tak dilibatkan di dalamnya. Wakil Komandan Satuan Tugas Penerangan PDMD Letkol CHB Firdaus mengatakan, pembentukan tim ini dilakukan berdasarkan sejumlah analisis. Di antaranya kecenderungan karakteristik warga Aceh zaman dulu yang masih melekat di zaman kini. “Orang Aceh zaman dulu yang ketika hendak berperang seringkali dimotivasi, salah satunya dengan syair-syair yang sifatnya heroik," ujarnya.
Berdasar hasil seleksi itulah, PDMD memanggil sejumlah produser, penyanyi, dan pencipta lagu. Namun meski lagu-lagu Nyawoung disinyalir PDMD sebagai lagu yang mengandung propaganda GAM, Joe sebagai produsernya tak dipanggil. Komunitas Nyawoung sendiri memang tak bermarkas di Aceh, melainkan di Jakarta.
Komandan tim bentukan PDMD untuk operasi kaset dan video compact disk (VCD) lagu Aceh Letkol Jerry Patras mengatakan, maksud pemanggilan tersebut tak lain untuk memberi masukan dan berkonsultasi. “Kami tidak melakukan pelarangan!” tegasnya.
Hal tersebut diakui Yusbi Yusuf. Katanya, yang dilakukan di gedung Media Center Dinas Infokom saat itu adalah klarifikasi atas sejumlah lagu yang diperkirakan berisi propaganda GAM.
Pada pertemuan pertama, 4 November 2003, sekitar 20 produser dikumpulkan. Ada tiga buah lagu yang dianggap bermasalah, yakni “Nanggroe Muerdeka“ karya Yusbi Yusuf, “Ujung Blang” karya penyanyi Kadri, dan “Peristiwa Guha Tujuh” yang diproduksi Nakri Production.
Yusbi mengaku kaget saat kali pertama menerima surat pemanggilan bernomor 01/TCV/2003 dari PDMD. “Untungnya di bawah surat itu disebut Infokom juga kan? Kalau surat itu hanya pemanggilan dari PDMD saja? Wahh…”
Semua orang di Aceh tahu kalau setiap pemanggilan dilakukan PDMD maka pemanggilan itu bersifat kriminal atau sesuatu yang mengarah pada kekerasan. Sekali pergi, kebanyakan jarang ada yang kembali.
Selama proses penelitian tim bentukan PDMD, Yusbi kebat-kebit dan sudah membayangkan kalau enam album miliknya yang berjumlah 10 ribu kaset bakal ditarik dari pasaran. Namun setelah klarifikasi dengan PDMD, rupanya terjadi salah tafsir atas “Nanggroe Meurdeka,” lagu dalam album Musibah volume 5, yang diciptakan dan dilantunkan Yusbi. Tim penyeleksi mengira judul lagu itu berarti “Nanggroe Aceh Meurdeka.” Padahal, menurut Yusbi, tak ada maksud itu ketika menciptakannya. “’Nanggroe Meurdeka’ itu justru menggambarkan kalau Aceh itu amat sangat merdeka. Tidak ada hukum. Itu semacam kritik sosial. Sama sekali bukan provokasi, propaganda, atau apapun yang ditafsirkan oleh berbagai kalangan. Menurut saya jauh sekali dari permintaan Aceh Merdeka.”
Mari kita simak syairnya:
Keubit Aceh nyoe merdeka/ Cukop bebaih hana bataih hukom tanlena/ Soe nyang beuhe soe nyang teuga, nyang nyang mat kuasa/ Rakyat jelata nyang tanggong bencana (Betul Aceh ini Nanggroe merdeka/ Cukup bebas, tanpa batas, hukum pun telah tiada/ Siapa yang berani, siapa yang kuat, dia yang pegang kuasa/ Rakyat jelata yang menanggung bencana)
Nak teumeutet nak seumupoh hana le so tham/ Tan keunong hukoman ureung durjana/Rumoh ditto harta jicok ureung jitikam/pelanggaran hana le jinietna (Mau membakar, hendak membunuh tak ada yang larang/ Tak pernah kena hukuman orang durjana/ Rumah dibakar, harta dirampas, orang ditikam/ Pelanggaran hak asasi manusia tak dihiraukan)
Setelah klarifikasi, di akhir pertemuan Jerry Patras menyatakan, memberi waktu dan kesempatan kepada para produser untuk menarik sendiri kaset yang menurut mereka dianggap bermasalah.
Pada pertemuan kedua, 13 November, yang dihadiri produser, penyanyi, dan pencipta lagu, dibahas tentang evaluasi dan rencana penarikan kaset serta VCD lagu-lagu yang terindikasi mengandung propaganda. Jerry Patras kini mengeluarkan blacklist sejumlah lagu yang dilarang beredar. Katanya, berdasarkan penyelidikan tim penyeleksi syair bentukan PDMD, ada lima lagu yang terindikasi dan harus ditarik dari pasar. Lagu-lagu tersebut adalah “Arakundoe” karya Yusbi Yusuf, “Simpang KKA” karya A. Bakar Ar, “Ie Mata” karya Jamaluddin, “Komandan” karya Banta Yan, dan “Jafar Sidiq” karya Jamaluddin.
Selain itu, Jerry Patras menilai sampul-sampul kaset yang dianggap bisa memancing dan mengungkit luka hati korban kemanusiaan di Aceh. Misalnya, ditemukan beberapa sampul kaset yang memuat foto-foto tragedi berdarah. Jerry Patras juga menyesalkan pemberitaan sejumlah media nasional yang dianggapnya berlebihan terhadap pemanggilan para seniman Aceh.
Tak mau ambil risiko, Yusbi menarik album Tragedi Arakundoe, yang di dalamnya terdapat lagu “Arakundoe,” miliknya. Alasannya sama seperti dengan Joe ketika memutuskan untuk tak memproduksi kembali album Nyawoung: supaya tak berdampak politis, biar tak meruncing. Yusbi juga mengaku cukup takut. Tapi dia masih berniat merilis album itu lagi, tanpa lagu “Arakundoe” yang digantinya dengan lagu baru yang akan diciptakannya.
Dampak lebih besar, seperti diungkapkan seorang produser lagu Aceh yang ogah ditulis identitasnya dalam suatu wawancara di acehkita.com, turun kegairahan mencipta lagu. “Padahal pasar memang minta lagu-lagu yang semacam itu kok. Mereka menerima dengan baik. Jika tidak ada permintaan ya enggak mungkin diproduksi, enggak bakal laku,” ujarnya.
Tak berselang setelah pertemuan itu, sejumlah seniman dari tujuh kabupaten di Aceh yang mengikuti pertemuan dengan PDMD berkumpul di rumah makan Aceh Cirasa menjelang buka puasa. Sebuah dialog dibuka pukul 16.00. Sudah lama para produser di Aceh menyadari perlunya sebuah organisasi sebagai tempat berhimpun dan menyalurkan aspirasi. Mereka juga merasa hak-hak penyanyi dan produser di Aceh belum terlindungi. Misalnya kasus pembajakan terhadap VCD lagu “Nurbanath Arhas” dari Takengon. Meski si pembajak tertangkap tangan, tapi pengadilan hanya menjatuhkan vonis tujuh hari penjara.
Selain itu, mereka juga menyadari tak punya akses dan kekuatan terhadap kebijakan penguasa setempat berkenaan dengan seni. Ini bisa dilihat dari keabsenan seniman Aceh dalam tim penyeleksi syair yang ironisnya, dampaknya sangat berpengaruh pada kehidupan berkesenian di Aceh.
Dari alasan-alasan itulah seluruh produser dan penggiat seni di Aceh sepakat membentuk Asosiasi Industri Rekaman Aceh. Ketuanya Yusbi Yusuf, pemilik Pas Record yang memang sudah malang-melintang di industri musik di Aceh.
Mendengar pemanggilan sejumlah rekannya, di Jakarta Joe menulis sebuah artikel tentang kondisi Aceh dan berkeseniannya, serta perjalanan pelarangan seni di Aceh. Artikel itu dimuat di acehkita.com. Hanya saja, meski pemanggilan itu jelas berupaya menghambat kreativitas, Joe melihat ada perbaikan yang dilakukan penguasa setempat. “Setidaknya sekarang tercipta dialoglah! Tidak main bredel seperti perlakuan kepada album Nyawoung saya dulu, kan?” ujarnya.
Di Jakarta Joe dan kawan-kawannya di Komunitas Nyawoung sering berkumpul di Taman Mini Indonesia Indah. Tepatnya di anjungan Nanggroe Aceh Darussalam. Setidaknya ada 50 orang yang bergabung dengan komunitas ini. Itu termasuk 13 seniman tradisi Aceh yang secara bergantian manggung untuk Nyawoung.
Ketika ditanya apakah tak khawatir Nyawoung dianggap sebagai komunitas provokator dari Jakarta yang mengatasnamakan seni, Agam menjawab dengan tenang, “Mereka bisa lihat, kita enggak bikin bom kok! Kita bikin musik Aceh!”
Kini, tinggal bagaimana Joe, Agam, dan teman-temannya menghadapi tantangan ke depan yang tak ringan. Pasar musik Aceh, menurut Yusbi Yusuf, cukup jenuh dengan lagu-lagu heroik atau patriotik. Meski segmen pasarnya masih tetap ada, tapi sekarang orang lebih cenderung mendengarkan lagu-lagu Aceh populer. Misalnya lagu “Marcelina” yang dilantunkan Ramli, atau lagu-lagu bernafaskan Islam seperti lagu “Ainul Mardhiah” yang dinyanyikan Rafli. Dua penyanyi muda itu tengah digandrungi di Aceh saat ini.
Tapi Joe sendiri tak mau hanya terfokus ke Aceh. Dia mengaku ingin membuat musik Aceh di Amerika atau Inggris. “Itu yang orang mau kan? Orang mau dengar apapun yang berbau luar negeri di sini. Kita juga pasti didengar, asalkan bikinnya di sana kan?” ujarnya berapi-api, meski dia sadar dengan keterbatasan dana untuk mewujudkan keinginan itu. *
*) Ucu Agustin adalah kontributor Aceh Feature di Jakarta
sumber asli artikel
http://www.acehfeature.org/index.php/site/detailartikel/387/Dendang-Nyawoung-untuk-Tanah-Rencong/
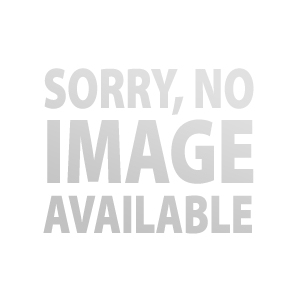
0 comments:
Post a Comment
komentar anda...